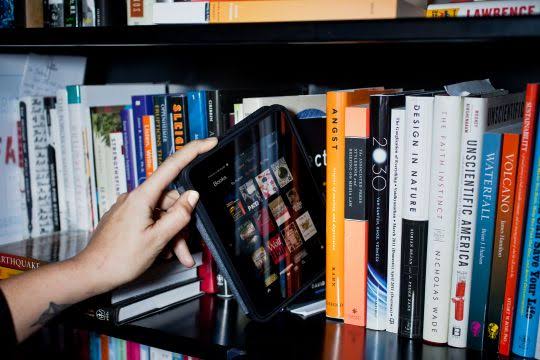Oleh: Deddy Mulyana
Artikel Surya Darma Hamonangan berjudul ”Jerumus Scopus” (Kompas, 11/3/2019) secara implisit mempertanyakan kredibilitas publikasi ilmiah di jurnal internasional terindeks Scopus (selanjutnya disebut artikel Scopus), yang selama ini menjadi acuan Kemristek dan Dikti. Menurut Hamonangan, perusahaan Elsivier dan Basis Data Scopus, yang dinaunginya selama ini ”jauh dari keterbukaan ilmiah dan keadilan sosial.”
Sejumlah akademisi kita yang skornya tinggi di Science and Technology Index (SINTA) Kemristek dan Dikti (yang dikalkulasi berdasarkan jumlah karya ilmiah yang diterbitkan dan sitasi yang dihitung oleh Google Scholar dan Scopus), ternyata menjadi manipulator Scopus, antara lain dengan menjadi calo Scopus, membuat artikel Scopus dengan me-”maklon”- kannya kepada orang lain dan melakukan sitasi karya sendiri secara berlebihan, sehingga akhirnya didaftarhitamkan oleh kementerian terkait serta diusir dari SINTA. Jika sebagian artikel Scopus itu ternyata tidak se-”bersih” dan se-”ilmiah” yang kita duga, lantas apakah kewajiban seorang doktor menulis artikel Scopus untuk menjadi profesor atau kewajiban seorang kandidat doktor untuk menulis artikel serupa agar lulus doktor masih relevan?
Prestasi akademisi seharusnya tak melulu diukur berdasarkan artikel Scopus, tetapi juga berdasarkan buku bermutu yang ditulisnya. Sayangnya, selama ini buku dianggap ”sebelah mata” oleh Kemristek dan Dikti juga oleh banyak perguruan tinggi yang menganggap artikel Scopus itu lebih bergengsi. Akibatnya, sejumlah doktor yang sebenarnya produktif menulis buku bermutu gagal menjadi profesor karena tidak menulis artikel Scopus.
Buku sebagai karya ilmiah tetap penting bagi dunia akademik, kalau tidak lebih penting dibandingkan dengan artikel Scopus yang saat ini ”digilai” akademisi Indonesia, asal ditulis dengan serius, berdasarkan sejumlah kriteria baku, termasuk referensinya yang mutakhir (dan berbahasa asing jika diperlukan). Buku seperti ini lazimnya juga mencakup hasil penelitian (metariset) yang menunjukkan kepakaran penulisnya.
Kapitalisme pengetahuan
Di Mesir, misalnya—seperti diutarakan seorang sejawat dosen yang lulusan Mesir—seorang doktor menjadi profesor berdasarkan mekanisme akademis tersebut, lewat penulisan buku bermutu dan artikel penelitian atau pemikiran berbahasa Arab. Bukan berdasarkan publikasi artikel Scopus berbahasa Inggris yang dianggap penghambaan terhadap imperialisme dan kapitalisme pengetahuan alih-alih sebagai penerbitan karya ilmiah.
Lagi pula kualitas karya ilmiah mestinya harus diukur bukan saja berdasarkan substansi dan metodenya, melainkan juga kemanfaatannya bagi publik. Tak mengherankan jika Khaliq ur Rehman Cheema, akademisi di Wuhan University of Technology Tiongkok, mengatakan, ”Buku teks yang menciptakan nilai dan berkontribusi dalam pengetahuan lebih berharga daripada artikel jurnal.” Benar apa yang disitir Hamonangan, berdasarkan Deklarasi Penilaian Riset yang diluncurkan di San Francisco tahun 2012, setiap karya hasil penelitian perlu dinilai berdasarkan kualitas karya itu sendiri alih-alih berdasarkan tempat di mana karya itu diterbitkan.
Martin Davis, seorang profesor di Universitas Melbourne, mengatakan bahwa buku teks tidak mudah ditulis. ”Jauh lebih sulit menulis untuk khalayak biasa atau mahasiswa tulisannya harus renyah, jelas, dan menarik. Kontras dengan itu, dalam menulis untuk sejawat orang bisa mengabaikan rincian (mereka telah mengetahuinya), dan menulis dengan gaya akademik yang canggih. Ini jauh lebih mudah dan lebih alamiah bagi akademisi. Saya baru saja merampungkan sebuah buku tentang keterampilan belajar bagi mahasiswa pasacasarjana internasional. Ini merupakan salah satu hal tersulit yang pernah saya lakukan dan itu memakan waktu bertahun-tahun,” tulis Martin. Jangan heran jika sebagian akademisi kita merasa lebih bangga sebagai penulis buku yang dibaca luas di dunia akademik daripada penulis artikel Scopus yang jarang atau tak pernah diakses mahasiswanya, bahkan sejawatnya.
Sebuah buku yang mengupas sejarah dan perkembangan suatu bidang ilmu yang ditulis bertahun-tahun boleh jadi jauh lebih berbobot daripada sebuah artikel Scopus bersifat fragmentaris berdasarkan teori dan metode tertentu yang ditulis beberapa bulan, apalagi jika artikel tersebut kurang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh adalah Pengantar Antropologi karya Koentjaraningrat atau Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo yang kini klasik dan legendaris. Sekarang kita jarang menemukan buku-buku komprehensif seperti itu karena akademisi kita dituntut dan lebih termotivasi menulis artikel Scopus.
Sejumlah akademisi atau peneliti asing pun berprestasi dan tersohor karena buku-buku mereka, seperti Emile Durkheim mengenai bunuh diri, Edward Said mengenai orientalisme, Stephen Littlejohn mengenai teori komunikasi, atau John Creswell mengenai metodologi penelitian kualitatif. Pada era digital 4.0 yang menyediakan mahadata (big data), para peneliti—terutama peneliti ilmu sosial dan humaniora—tak harus pergi ke lapangan, tetapi cukup duduk di depan laptop mereka untuk menghasilkan karya bermutu.
Pada masa lalu, mungkin juga kini, sejumlah akademisi kita layak menjadi profesor, meskipun mereka tidak bergelar doktor. Jakob Sumardjo adalah seorang profesor di Fakultas Seni Rupa ITB, meskipun bergelar S-1. Namun, siapa yang meragukan kepakarannya sebagai Guru Besar Filsafat (seni/budaya) Indonesia dan pengamat sastra Indonesia, sebagaimana yang terlihat dalam beberapa bukunya dan banyak artikelnya di media cetak, termasuk di Kompas.
Kini, karena gelar doktor disyaratkan untuk menjadi guru besar, akademisi yang bergelar S-2—apalagi S-1—tak bisa lagi menjadi profesor. Namun, syarat menulis artikel Scopus seharusnya bisa diganti dengan syarat menulis buku bermutu, seperti yang diterapkan oleh sejumlah perguruan tinggi di luar negeri. Mekanisme ini terutama sangat relevan bagi akademisi yang mendalami ilmu-ilmu sosial dan humaniora, khususnya yang menggunakan perspektif interpretif atau kritis dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ilmiah berbasiskan ”kesatuan ilmu” seperti dalam ilmu alam (fisika, kimia, dan sejenisnya) memang lebih layak ditulis dalam bentuk artikel ilmiah, sementara hasil penelitian ilmu sosial lebih cocok menjadi buku, karena sifat ilmu sosial yang holistik, rumit, kontekstual, dan bahkan lokal.
Banyak dikritik
Kebergantungan perguruan tinggi kita pada publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi banyak dikritik belakangan ini karena hal itu juga telah mengorbankan pentingnya perkuliahan (tatap-muka) dengan mahasiswa. Ada sejumlah dosen yang meskipun skor (h-index) Google Scholar dan skor SINTA-nya tinggi, ternyata mereka malas mengajar di ruang kuliah, malah cara mengajarnya pun dinilai buruk.
Kritik lain terhadap kecenderungan berlebihan dalam publikasi ilmiah adalah kekurangmampuan akademisi untuk beradaptasi dengan dunia luar yang begitu pesat, yang sering dikaitkan dengan Revolusi Industri 4.0. Kelengahan kita pada perkembangan peradaban masyarakat dengan terlalu fokus pada publikasi ilmiah yang elitis membuat kita semakin tersisih dari dunia nyata. Penelitian yang bermanfaat pada era digital ini adalah penelitian yang bisa langsung dirasakan masyarakat luas, terutama masyarakat lokal, bukan penelitian di ”awang-awang.” ***
” Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, artikel ini sudah terbit di Kompas“